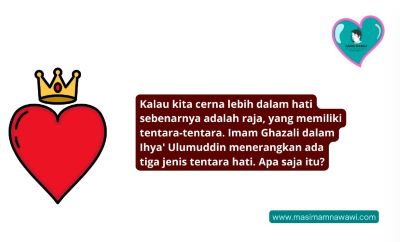BERITAUNGGULAN.COM, JAKARTA – Jumat (03/10/2025) Kepala sekolah sering disebut sebagai “nahkoda” pendidikan. Dari tangan merekalah arah kebijakan, iklim belajar, hingga semangat guru dan siswa bisa bergerak. Namun, apakah kepemimpinan kepala sekolah di Indonesia hari ini benar-benar sejalan dengan teori kepemimpinan yang kita pelajari di kelas? Atau justru tersandera oleh beban administrasi dan tekanan birokrasi?
Artikel ini ditulis oleh: Trisia Loli Maulana (Diajukan untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Kepemimpinan & Pengambilan Keputusan, Dosen Pengampu: Dr. Dr. Dra. Hj. Neng Nurhaemah, M.Pd., S.Pd.)
Teori di Ruang Kuliah: Dari Transformasional hingga Servant Leadership
Dalam teori kepemimpinan pendidikan, kita mengenal sejumlah pendekatan yang ideal:
- Kepemimpinan transformasional, yang menekankan visi besar, motivasi, dan perubahan budaya sekolah (Bass, 1990).
- Kepemimpinan instruksional, di mana kepala sekolah fokus mengarahkan kualitas pembelajaran guru dan hasil belajar siswa (Hallinger, 2011).
- Kepemimpinan situasional, yang menyesuaikan gaya memimpin sesuai kondisi dan kebutuhan bawahan (Hersey & Blanchard, 1988).
- Servant leadership, yang menekankan kepemimpinan berbasis pengabdian, pelayanan, dan pemberdayaan komunitas sekolah (Greenleaf, 1977).
- Distributed leadership, di mana kepemimpinan tidak hanya bertumpu pada kepala sekolah, tetapi dibagi bersama guru, staf, dan bahkan siswa (Spillane, 2006).
Di atas kertas, teori-teori ini terdengar indah. Kepala sekolah bukan hanya manajer, melainkan inspirator yang mendorong lahirnya inovasi dan kemandirian. Namun, apakah realitas di lapangan sejalan dengan gagasan ini?
Realitas di Lapangan: Kepala Sekolah yang Terjebak Administrasi
Sayangnya, banyak kepala sekolah di Indonesia masih terkunci dalam logika birokrasi.
Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 60% waktu kepala sekolah tersita untuk urusan administratif, mulai dari laporan penggunaan Dana BOS hingga persiapan akreditasi. Tidak heran jika fungsi kepemimpinan instruksional yang seharusnya fokus pada pembelajaran sering terabaikan.
Fenomena ini diperkuat oleh penelitian Suyanto & Jihad (2021) yang menemukan bahwa sebagian besar kepala sekolah di daerah mengaku kesulitan menyeimbangkan peran administratif dengan tugas pedagogis. Akibatnya, kepemimpinan transformasional yang mendorong visi bersama dan inovasi sering hanya menjadi jargon.
Kesenjangan Teori dan Praktik
Kesenjangan antara teori kepemimpinan dan praktik di lapangan bisa dilihat dari beberapa aspek:
- Visi yang Redup oleh Rutinitas
Banyak kepala sekolah memiliki visi bagus, tetapi energi mereka habis untuk mengurus dokumen. Akhirnya, visi hanya berhenti di papan mading, tidak menembus ruang kelas. - Kepemimpinan Instruksional yang Lemah
Idealnya, kepala sekolah menjadi coach bagi guru. Namun realitas menunjukkan supervisi kelas sering formalitas belaka, lebih banyak mengisi formulir ketimbang memberi umpan balik yang membangun. - Kurangnya Distribusi Kepemimpinan
Teori distributed leadership menekankan pentingnya berbagi tanggung jawab. Sayangnya, di banyak sekolah masih berlaku pola hierarkis: kepala sekolah sebagai pengendali tunggal, guru sebagai pelaksana. Akibatnya, kreativitas guru sering terhambat. - Tekanan Logika Pasar dan Kompetisi
Dalam beberapa tahun terakhir, logika pasar juga ikut merasuk ke dunia sekolah. Banyak kepala sekolah sibuk membangun “branding” sekolah untuk menarik siswa baru, kadang lebih sibuk promosi di media sosial ketimbang memperkuat mutu pembelajaran.
Cahaya di Tengah Tantangan: Praktik Baik di Indonesia
Meski demikian, tidak sedikit kepala sekolah yang berhasil menerjemahkan teori menjadi praktik nyata.
Misalnya, di program Sekolah Penggerak Kemendikbudristek, ada kepala sekolah yang berani mengurangi jam rapat administratif dan menggantinya dengan forum refleksi pembelajaran bersama guru. Di sejumlah sekolah dasar di Yogyakarta dan Jawa Barat, kepala sekolah bahkan membentuk learning community di mana guru saling mengobservasi praktik mengajar dan memberi umpan balik.
Contoh lain datang dari SMAN 2 Semarang, di mana kepala sekolah mendorong guru memimpin proyek lintas mata pelajaran berbasis isu lokal—dari lingkungan hingga kewirausahaan. Praktik ini menunjukkan bagaimana distributed leadership dan kepemimpinan transformasional bisa berjalan seiring.
Solusi dan Rekomendasi: Mengembalikan Kepala Sekolah ke Ruh Kepemimpinan
Jika kita ingin kepala sekolah benar-benar menjadi pemimpin organik yang lahir dari komunitas dan mampu menggerakkan perubahan, beberapa langkah strategis bisa ditempuh:
- Reduksi Beban Administrasi
Pemerintah perlu mempercepat digitalisasi sistem pelaporan dan mengurangi dokumen berlapis. Kepala sekolah harus diberi ruang lebih besar untuk mendampingi guru dan siswa. - Pelatihan Kepemimpinan Berkelanjutan
Bukan sekadar workshop singkat, tetapi coaching dan pendampingan jangka panjang yang menekankan pada praktik instruksional, manajemen perubahan, dan kepemimpinan moral. - Distribusi Kepemimpinan
Budaya hierarki tunggal harus bergeser. Guru, siswa, dan bahkan orang tua perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Ini bukan hanya soal efisiensi, tapi juga membangun rasa memiliki. - Menguatkan Kepemimpinan Moral
Kepala sekolah perlu menegaskan diri bukan sekadar pejabat administratif, melainkan pendidik publik yang berani melawan logika pasar dan mengembalikan sekolah sebagai ruang pembentukan manusia seutuhnya. - Membangun Jejaring Komunitas
Kepala sekolah sebaiknya aktif menjalin kerja sama dengan lembaga luar, komunitas lokal, dan dunia usaha. Dengan begitu, sekolah tidak hanya berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem perubahan sosial.
Teori kepemimpinan yang kita pelajari di kelas bukan sekadar bahan ujian, melainkan cermin untuk menilai realitas pendidikan kita. Saat ini, kepala sekolah di Indonesia menghadapi dilema: di satu sisi dituntut menjadi manajer birokrasi, di sisi lain diharapkan menjadi pemimpin pembelajaran.
Jika kita mampu mengurangi beban administratif, memperkuat pelatihan kepemimpinan, dan menumbuhkan budaya partisipatif, kepala sekolah dapat kembali ke ruh sejatinya: pemimpin moral yang menginspirasi guru, menggerakkan siswa, dan menjadikan sekolah sebagai lokus perubahan sosial.
Karena pada akhirnya, kepemimpinan kepala sekolah bukan soal kekuasaan, tetapi tentang tanggung jawab moral untuk menghadirkan pendidikan yang adil, bermakna, dan membebaskan bagi semua anak Indonesia.
Referensi
- Bass, B. M. (1990). From transactional to transformational leadership: Learning to share the vision. Organizational Dynamics.
- Hallinger, P. (2011). Leadership for learning: Lessons from 40 years of empirical research. Journal of Educational Administration.
- Spillane, J. P. (2006). Distributed leadership. Jossey-Bass.
- Suyanto & Jihad, A. (2021). Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia. Jurnal Manajemen Pendidikan.
- Kemendikbudristek (2023). Laporan Tahunan Pendidikan Indonesia.
- Greenleaf, R. K. (1977). Servant Leadership. Paulist Press.